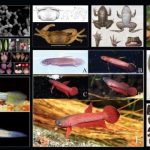Jakarta (Greeners) – Di banyak kota besar Indonesia, makna dari mobilitas masih kerap dipahami secara sempit. Mobilitas hanya menjadi urusan memindahkan kendaraan bermotor dari satu titik ke titik lain, sementara manusia sebagai subjek utama mobilitas justru terpinggirkan.
Dari paradigma tersebut mengakibatkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur pun lebih sering berfokus pada kelancaran mobil dan sepeda motor. Padahal, mobilitas seharusnya memikirkan bagaimana orang berjalan kaki, bersepeda, dan mengakses transportasi publik dengan aman, layak, dan berkeadilan.
Berdasarkan makna dasarnya, mobilitas sejatinya tidak sesempit itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mobilitas merupakan gerakan berpindah-pindah atau kesiapsiagaan untuk bergerak.
Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah berpindah atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dari sini, jelas bahwa mobilitas berbicara tentang manusia dan pergerakannya dalam ruang hidup sehari-hari, bukan hanya soal kendaraan yang melintas di jalan.
Pemaknaan inilah yang kini kembali menuai kritik, salah satunya oleh Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Kota Bandung. Kota yang terkenal sebagai kota kreatif hingga kota pesepeda ini justru berhadapan dengan permasalahan mobilitas yang kian rumit. Jalanan di Kota Kembang itu semakin padat dengan kendaraan bermotor hingga menimbulkan banyak kemacetan.
Berdasarkan TomTom Traffic Index (2024), Bandung menempati peringkat ke-12 sebagai kota termacet di dunia. Sementara itu, Dinas Perhubungan mencatat bahwa jumlah kendaraan pribadi di kota ini hampir menandingi jumlah penduduknya. Sekitar 2,2 juta kendaraan bermotor dan mobil bergerak di jalan-jalan Bandung, berbanding dengan 2,4 juta jiwa penduduk.
Ketua Bike to Work Bandung, Moch Andi Nurfauzi, menilai persoalan ini berakar dari kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah masih memahami sekadar memindahkan kendaraan bermotor dari satu titik ke titik lainnya, bukan memikirkan bagaimana manusia berpindah dan menjalani aktivitas hariannya. Cara pandang inilah yang, sejak awal, membuat perencanaan mobilitas kerap meleset dari kebutuhan warga.
“Padahal, manusia yang bermobilitas memiliki latar belakang, kebutuhan, dan kondisi yang beragam, mulai dari warga yang tinggal di wilayah pinggiran kabupaten hingga mereka yang harus beraktivitas di pusat kota. Karena paradigma ini keliru sejak awal, perencanaan mobilitas pun gagal menjawab kebutuhan nyata masyarakat.”
Kuasa Kendaraan Bermotor
Dari kacamata Andi, dalam konteks Bandung maupun kota-kota besar lain di Indonesia, kegagalan pemerintah dalam memudahkan mobilitas warganya muncul dari gejala yang sama. Ia menyebutnya sebagai dominasi rezim automobility.
Dalam rezim tersebut, sistem transportasi masih menempatkan kendaraan bermotor sebagai pusat dari seluruh kebijakan. Ketika kemacetan terjadi, solusinya hampir selalu serupa pelebaran jalan, pembangunan jalan layang, atau infrastruktur lain yang justru semakin memanjakan kendaraan pribadi. Sementara itu, penguatan transportasi publik yang terintegrasi, serta penyediaan infrastruktur yang aman bagi pejalan kaki dan pesepeda, belum menjadi prioritas utama.
Kondisi ini, menurut Andi, tercermin jelas di Kota Bandung. Jika dibandingkan dengan Jakarta, Bandung bahkan dinilai tertinggal jauh dalam hal transformasi mobilitas berbasis transportasi publik.
Meski Bandung telah memiliki layanan transportasi bus seperti Metro Jabar Trans dan Damri, Andi menilai sistem tersebut belum terkoneksi dengan baik. Perbedaan sistem pembayaran, rute yang tumpang tindih, hingga tidak adanya integrasi antarlayanan membuat transportasi publik belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas warga secara menyeluruh.
“Keberadaan bus sering kali hanya dipandang sebatas ‘ada’, tanpa evaluasi serius apakah layanan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Bandung Raya,” ujarnya.
Anggaran belanja infrastruktur di kota ini pun masih didominasi oleh proyek-proyek yang bertujuan melancarkan lalu-lintas kendaraan pribadi, bukan memperkuat konektivitas transportasi umum atau memperbaiki fasilitas berjalan kaki dan bersepeda.
Selain itu, Andi bersama organisasinya, Bike to Work Bandung, banyak menemukan fasilitas pejalan kaki yang rusak. Contohnya trotoar di beberapa ruas jalan utama kerap terputus oleh parkir kendaraan atau akses bangunan komersial. Hal tersebut menyebabkan hak pejalan kaki kembali tergerus oleh kepentingan kendaraan bermotor.
Hal serupa terjadi pada fasilitas pesepeda. Pada 2025, lajur sepeda di Jalan BKR, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Supratman sudah tidak lagi ditemukan. Padahal, keberadaan lajur sepeda di kawasan tersebut merupakan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022.

Paradigma mobilitas di Bandung masih berpusat pada kendaraan bermotor. Foto: Argus FS (Bike to Work Bandung)
Bergantung pada Pengguna
Andi menekankan bahwa perancangan mobilitas di Bandung tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif. Sebab, pergerakan warga Bandung juga mencakup beberapa wilayah seperti ke Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Cimahi, hingga Bandung Barat. Maka dari itu, mobilitas di Bandung harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem.
Namun, dalam praktiknya, batas administratif justru sering jadi alasan pemerintah daerah untuk saling melempar tanggung jawab sehingga perencanaan mobilitas yang terintegrasi sulit terwujud.
Ia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang masih berbasis pada demand based policy. Dalam pendekatan ini, penyediaan fasilitas publik bergantung pada jumlah pengguna. Akibatnya, jalur sepeda atau trotoar sering kali tidak jadi prioritas dengan alasan “tidak ada penggunanya”.
“Penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda merupakan kewajiban pemerintah yang sudah diatur dalam regulasi, terlepas dari banyak atau sedikitnya pengguna. Infrastruktur seharusnya dibangun terlebih dahulu agar kebiasaan masyarakat dapat tumbuh, bukan sebaliknya.”
Menanti Sistem Transportasi Terintegrasi
Penyediaan fasilitas transportasi umum di Kota Bandung juga belum terintegrasi dan masif. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperparah kemacetan di kota ini semakin parah.
Akademisi sekaligus pengamat budaya urban, Jejen Jaelani menilai bahwa kondisi mobilitas di Kota Bandung selama dua dekade terakhir masih sangat berorientasi pada kendaraan pribadi. Sejak awal 2000-an, menurut dia, pemerintah tidak memiliki visi dan program yang jelas untuk membenahi transportasi publik.
Hal tersebut terlihat dari kembali menguatnya wacana pembangunan jalan tol dalam kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mobilitas masih berpihak pada mobil dan motor, bukan pada transportasi publik, pejalan kaki, maupun pesepeda.
Jejen melihat akar persoalan terkait mobilitas ini bukan bertumpu pada rendahnya penggunaan jalur pesepeda penggunaan jalur pejalan kaki dan sepeda. Namun, permasalahannya terletak pada infrastruktur yang aman, terkoneksi, dan fungsional.
“Jalur sepeda di Bandung selama ini lebih diperlakukan sebagai fasilitas rekreasi, hanya hadir di titik-titik tertentu seperti Jalan Dago, Diponegoro, dan Asia Afrika, tanpa konektivitas antarkawasan. Akibatnya, warga termasuk orang tua enggan membiarkan anak-anak bersepeda karena kondisi jalan yang berbahaya.”
Ia mencontohkan kota-kota besar seperti Tokyo, di mana sepeda menjadi bagian dari sistem mobilitas harian yang terintegrasi dengan transportasi publik. Warga dapat bersepeda dari rumah ke stasiun, menyimpan sepeda dengan aman, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan kereta.
Selain itu, ia juga melihat Jakarta yang kini perlahan mengalami perubahan perilaku mobilitas warganya. Perubahan ini terjadi setelah jaringan Transjakarta, KRL, dan sistem integrasi transportasi terus berkembang selama dua dekade terakhir.
Menurutnya, konsep semacam ini belum terwujud di Bandung. Hal itu imbas ketiadaan fasilitas pendukung, seperti parkir sepeda yang aman di stasiun dan terminal. Untuk itu, perubahan perilaku masyarakat pun tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai.
Jejen menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa terus menunggu budaya terbentuk secara organik. Pemerintah harus segera menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah, dan terintegrasi supaya mobilitas ramah lingkungan dan berkelanjutan yang dicita-citakan bisa tercipta.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia