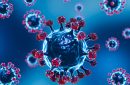Jakarta (Greeners) – Sumber daya genetik menjadi isu utama dalam Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang sekarang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Rancangan UU ini diharapkan mampu menjadi pengganti UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan draft revisi UU nomor 5 tahun 1990 perlu mencakup perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari keanekaragaman hayati Indonesia.
Kepala sub Direktorat Sumber Daya Genetik KLHK Indra Exploitasia Semiawan menyatakan bahwa tingkatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia harus dilihat mulai dari genetik, spesies, dan ekosistem. Sedangkan potensi sumber daya genetik Indonesia bisa ditemui dalam tumbuhan, satwa, mikroba dan pengetahuan tradisional yang tersebar dalam kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi.
Saat ini, lanjutnya, potensi pencurian sumber daya genetik di Indonesia cukup rentan. Data KLHK hingga tahun 2014, peneliti asing sebanyak 24 persen menjadi pihak kedua yang terbanyak meneliti terhadap satwa liar di Indonesia. Angka akses permintaan untuk penelitian sumber daya genetik tersebut masih bisa terus bertambah dan berjalan sementara aturan terhadap sumber daya genetik belum memadai.
“Bagaimana penegakan hukum, bagaimana status pemanfaatan sumber daya genetik yang sudah dibawa ke luar negeri, semua itu belum ada regulasinya,” ujar Indra dalam paparannya pada diskusi pakar yang diadakan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Jakarta, Selasa (12/01).

Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Direktur Program Tropical Forest Conservation Action Sumatera-KEHATI Samedi juga menambahkan bahwa masalah ekosistem dalam UU No. 5 Tahun 1990 masih belum mewakili ekosistem dalam kawasan konservasi. Padahal, ekosistem perlu dilindungi demi menjaga keberadaan ekosistem asli yang menjadi sumber plasma nutfah (kekayaan sumber daya genetik). Ia menyarankan ada penetapan keterwakilan ekosistem dalam suatu kawasan konservasi dan penetapan ekosistem bernilai penting di luar kawasan dengan tujuan agar kawasan di luar wilayah konservasi yang bernilai tinggi juga terlindungi.
Menurut Samedi, pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati tersebut harus memenuhi tiga pilar Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention of Biological Diversity) yang dikuatkan dengan Protokol Nagoya. Ketiganya adalah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatkan komponen keanekaragaman hayati yang lestari (berkelanjutan), pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik.
Pada UU No.5 Tahun 1990, menurut Harry Alexander, Praktisi Hukum Lingkungan dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, masih belum memasukkan pilar ketiga dari konvensi keanekaragaman hayati. Padahal Indonesia sudah meratifikasi Protokol Nagoya menjadi UU pada tahun 2013. Isu pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik, lanjutnya, adalah tujuan konvensi yang banyak ditolak negara maju.
“Dalam RUU ini, harus menambah pendekatan aspek pembagian keuntungan dari unsur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga lantaran sumber daya genetik di Indonesia tak bisa dilepaskan dengan hak kekayaan intelektual masyarakat,” tambahnya.
Saat ini, lanjutnya, sudah banyak peneliti asing yang memanfaatkan sumber daya genetik lokal yang berkualitas tinggi. Sementara dalam batang tubuh RUU justru masih kental tentang sumber daya genetik yang liar. Padahal sumber daya genetik lokal yang berkualitas tinggi secara perlahan sudah dikembangkan negara lain.
Ia memberi contoh embrio sapi Bali yang dibeli oleh Malaysia. Sapi bali, tuturnya, adalah sapi yang dagingnya paling baik di dunia. Sapi bali keturunan banteng dan banteng adalah satwa liar di Indonesia. Sementara ini malaysia yang impor. Ada juga tanah garapan di Cilembu disewakan kepada Jepang untuk penelitian ubi.
“RUU harus mampu melindungi sumber daya genetik lokal yang berkembang di masyarakat. Sebab sumber daya genetik lokal terancam punah jika tidak digunakan lagi. Hal itu terjadi jika banyak masuk produk budidaya impor yang lebih murah atau pihak asing menguasai teknologi budidaya sumber daya genetik lokal. Akibatnya masyarakat enggan memanfaatkan sumber daya genetik lokal, sehingga perlahan menghilang,” tukasnya.
Penulis: Danny Kosasih